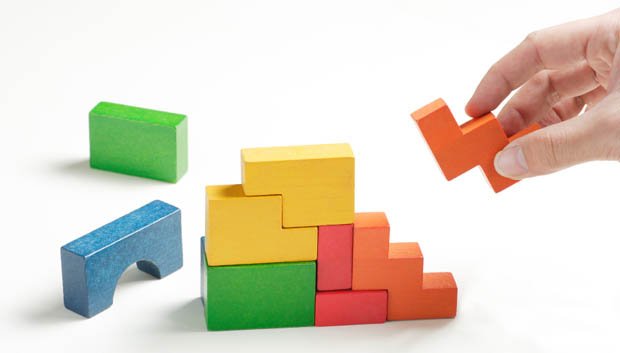
Civis 002/2013
Menegakkan Sistem Presidensiil
Dihadapan pemimpin redaksi berbagai media massa tgl 16 Juli 2013 yang lalu, Presiden SBY melemparkan lima masalah yang menjadi tantangan bangsa ke depan. Beliau antara lain mempertanyakan apakah kita memilih sistem presidensiil murni ataukah menerapkan sistem ketatanegaraan semi-parlementer? Apakah checks and balances yang dijalankan sekarang ini sudah tepat? Pada kesempatan itu Presiden SBY juga mengatakan masyarakat sering berharap agar Presiden bertindak seperti pada era otoritarian, padahal dalam era demokrasi sekarang, seharusnya Presiden (pemerintah) menggunakan kaidah demokrasi dan rule of law.
Tentu ada alasan mengapa beliau melontarkan masalah itu. Kelihatannya Pak SBY menilai sistem yang diterapkan sekarang ini tidak cocok. Secara umum, seperti pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu, sistem kita sering disindir sebagai sistem presidensiil rasa parlementer. Resminya sistem presidensiil tetapi prakteknya cenderung parlementer. Dalam banyak hal, presiden sebagai kepala eksekutif dianggap, misalnya dalam membentuk undang-undang, termasuk UU APBN, harus tunduk kepada DPR, dalam mengangkat Duta Besar harus mengikuti kemauan DPR yang melakukan fit and proper test atas calon Duta Besar, dalam mengangkat Panglima TNI dan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. Presiden sangat tergantung pada peta dukungan politik di parlemen (DPR). Sehingga Presiden SBY (terpaksa?) membangun kabinet koalisi dengan harapan partai-partai koalisi akan mendukung kebijakannya di DPR. Sedemikian, sehingga bandul kekuasaan yang tadinya amat besar pada presiden, sementara DPR dan yang lain lemah, berayun terlalu jauh menjadi DPR terlalu berkuasa dan kekuasaan Presiden tergerus hampir habis, lemah dan seperti disimpulkan konvensi Alumni Lemhanas 2007, tidak mangkus lagi.
Sementara pada pihak lain, ada pendapat bahwa sistem presidensiil dalam prakteknya, terutama negara dengan budaya politik yang belum cukup matang dan masyarakat sipil yang lemah, dengan mudah berubah menjadi sistem otoriter seperti terjadi pada masa lalu kita dan juga dibeberapa negara lain.
Melihat kenyataan itu, dipertanyakan apakah kita akan tetap mempertahankan sistem presidensiil atau mengubahnya menjadi sistem (semi-) parlementer dengan meng-amandemen lagi amandemen UUD 1945?
Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh, oleh karena amandemen konstitusi bukanlah hal yang tabu, perlu dipertanyakan apakah memang sistem presidensiil, bila diterapkan sebagaimana harusnya selalu akan atau selalu mudah menjadi otoritarian? Apakah sistem presidensiil memiliki potensi benefit yang melampaui potensi sisi negatifnya untuk kita sebagai negara berkembang yang besar dan amat majemuk? Selanjutnya, apakah sistem presidensiil yang dianut oleh UUD 1945 {Pasal 4 (1)} telah dilaksanakan sebagaimana harusnya? Atau apakah ada ketentuan dalam UUD 1945 atau apakah ada peraturan perundangan dan perangkat lain dibawah UUD yang menyimpang dari UUD 1945 yang tidak sesuai dengan sistem presidensiil itu?
Pertanyaan yang lain tentu adalah apakah sistem (semi-) parlementer cocok untuk kita, negara kesatuan yang besar dan amat majemuk serta masih tergolong negara berkembang?
Sistem Presidensiil Dan Sistem Kepartaian.
Proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung dalam satu rangkaian proses bertahap dari tahun 1999 sampai dengan 2002 (bukan dalam 4 kali amandemen), telah dengan sengaja memilih melanjutkan sistem presidensiiil, bukan sistem parlementer, karena berbagai pertimbangan. Disadari bahwa jumlah partai di Indonesia amat banyak (peserta pemilu 1999 48 parpol) sehingga ada anggapan lebih cocok untuk membangun sistem parlementer. Tetapi mengingat pengalaman sistem parlemen sebelumnya (1950-1957), dimana pemerintahan silih berganti jatuh-bangun dalam waktu singkat (6 kabinet dalam 7 tahun), penuh dengan goncangan politik dan karenanya tidak ada kabinet yang sempat berkarya, risalah amandemen UUD 1945 mencatat semua pihak memilih mempertahankan sistem presidensiil. Tidak ada yang memilih sistem parlementer. Tetapi, semua pihak juga menyadari bahwa sistem presidensiil ber-pontensi berubah menjadi otoriter, seperti pernah kita alami dimasa lalu dan juga oleh negara-negara lain.
Demikianlah sistem presidensiil telah dipilih karena dinilai lebih stabil dan berpeluang berprestasi karena masa jabatannya tertentu (fixed-term) dan kekuasaan eksekutif terpusat di tangan Presiden, sehingga harusnya lebih cekatan mengatasi berbagai masalah dan tantangan.
Tetapi perlu dicatat bahwa pilihan itu disertai disertai ketentuan lain untuk membatasinya (limitations of power), seperti negara hukum (rule of law) {Pasal 1 (2)}, hak asasi manusia (Pasal 28A-J), pembatasan masa jabatan maksimum 2 kali berturut-turut (Pasal 7), mekanisme checks and balances dalam sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan (separation and sharing of powers), seperti DPR dengan kekuasaan legislatif, anggaran dan pengawasan, dll (Pasal 20A) dan kekuasaan kehakiman yang merdeka {Pasal 24 (1)}, kekuasaan judicial review oleh Mahkamah Konsitusi (Paal 24C), BPK yang merdeka {Pasal 23E), pemilu dan pilpres langsung sebagai mekanisme sirkulasi kepemimpinan yang demokratis dan periodik (Pasal 6A & 22E), penegasan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi {Pasal 22E (3)}, dsb.
Demikian pula, risalah rapat amandemen mencatat bahwa fraksi-fraksi berkehendak untuk mengurangi jumlah partai politik dalam pemerintahan, untuk membangun sistem kepartaian majemuk-sederhana (simple multi-party system), dengan menerapkan ambang batas tertentu suara yang diperoleh parpol dalam pemilu (electoral threshold). Tata-cara pencalonan dan pemlihan presiden juga diatur sedemikian, diajukan dalam satu paket oleh parpol dan/atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pemilu {Pasal 6A (2)}, dimaksudkan agar penggabungan parpol terjadi berdasarkan kesepakatan visi dan misi, bukan sekedar koalisi yang transaksional bila dilakukan setelah pemilu. Political engineering itu dimaksudkan agar dalam beberapa kali pemilu, jumlah partai akan berkurang dan perilaku politiknya sesuai dengan sistem presidensiil. Dengan perkataan lain UUD 1945 juga mengandung langkah rekayasa yang perlu dilaksanakan untuk antara lain, membangun sistem kepartaian yang cocok.
Presiden Dan Parlemen.
UUD 1945 menetapkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dan satu masa jabatannya pasti, 5 tahun dan hanya boleh menjabat berturut-turut untuk 2 masa jabatan. Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR dan walaupun DPR dapat meminta MPR untuk memakzulkan Presiden/Wakil Presiden, tetapi yang berhak memberhentikannya adalah MPR, setelah Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa Presiden melanggar ketentuan UUD seperti yang dituduhkan DPR (Pasal 7a & 7B). Jadi, DPR tidak mudah menggoyang kedudukan Presiden.
Meskipun kewenangan membentuk undang-undang dipindahkan dari Presiden kepada DPR {Pasal 20 (1)}, namun Presiden tidak berada dibawah atau harus tunduk kepada DPR. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) hanya dapat ditetapkan menjadi undang-undang (UU) bila RUU itu telah dibahas bersama dan telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden {Pasal 20 (2)}. Dalam hal itu, DPR yang terdiri dari 560 anggota adalah satu lembaga dan seorang Presiden juga adalah satu lembaga, yang kedudukan dan suaranya seimbang dan sama kuat. Seandainya seluruh anggota DPR berpendapat A tetapi seorang Presiden tidak sependapat maka RUU itu tidak bisa ditetapkan menjadi UU. Artinya Presiden tidak harus tunduk kepada DPR. Demikian pula sebaliknya.
Pada masa reformasi, seorang Presiden pernah menyatakan tidak sepakat terhadap sebuah RUU walaupun DPR bersikeras menjadikannya sebagai UU (RUU Otorita Batam). Dengan demikian, untuk membuat UU, sebuah produk hukum tertinggi sesudah UUD, DPR dan Presiden harus bermusyawarah untuk sepakat, sebagaimana diarahkan oleh sila ke-4 Pancasila. Bila Presiden atau DPR ingin memenangkan sebuah RUU, harus dilakukan pendekatan dan lobby intensif, terbuka atau tertutup, untuk meyakinkan Presiden atau meyakinkan mayoritas anggota DPR. Dalam hubungan itu, dukungan rakyat yang diperoleh Presiden pada waktu pilpres, harus dapat dijadikan modal politik. Sikap seperti itu akan dapat mengatasi kemungkinan kebuntuan (grid-locked) atas sebuah RUU, apalagi UUD memberi kewenangan tambahan kepada Presiden untuk mengatasi sebuah kebuntuan (Pasal 22).
Apabila sebuah RUU telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, maka RUU itu harus diundangkan oleh Presiden sebagai kepala negara. Dimasa lalu pernah terjadi ada RUU yang sudah disepakati DPR dan Presiden (RUU Penyiaran) tidak diundangkan oleh Presiden, sehingga RUU itu tidak pernah menjadi UU. Untuk mencegah hal itu dan untuk menegaskan kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR, maka bila dalam masa 30 hari RUU yang sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden tidak diundangkan oleh Presiden, maka RUU itu otomatis sah menjadi UU {Pasal 20 (5)}. Jadi, tidak benar anggapan bahwa DPR dapat memaksakan sebuah RUU menjadi UU tanpa persetujuan Presiden. Dengan proses seperti itu, amandemen tidak perlu memberikan hak veto kepada Presiden, karena memang tidak diperlukan lagi dan juga tidak sesuai dengan semangat musyawarah.
Dalam sebuah diskusi studi banding di Washington, seorang pakar tatanegara AS mengakui bahwa sistem veto mereka berpotensi menimbulkan beban politik yang berat manakala seorang presiden mem-veto sebuah UU yang telah disahkan oleh Kongres (House atau Senate). Oleh karena itu, pada prakteknya, Presiden dan Kongres AS selalu melakukan lobby yang intensif agar tercapai kesepakatan sebelum sebuah RUU disahkan menjadi UU.
Duta Besar adalah wakil bangsa dan negara dan wakil pribadi Presiden di negara sahabat. Pada masa lalu tidak jarang terjadi pos duta besar itu hadiah bagi orang tertentu atau juga tempat pembuangan orang tertentu. Oleh karena itu amandemen UUD menegaskan bahwa dalam mengangkat duta besar presiden perlu memperhatikan pertimbangan DPR {Pasal 13 (2)}. Tapi prakteknya, secara sepihak DPR mengartikan pertimbangan itu sebagai fit and proper test. Seolah-olah DPR yang menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi duta besar. Pada masa lalu, walaupun pertimbangan DPR diperhatikan, tetapi Presiden-lah yang menetapkan duta besar sesuai dengan kebijakannya. Tetapi belakangan kelihatannya Presiden mengikatkan diri pada hasil fit and proper test DPR.
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4) dan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10). Pada kenyataannya, untuk mengangkat Kapolri dan Panglima TNI, UU mengharuskan Presiden memperoleh persetujuan DPR (UU no. 2/2002 tentang Kepolisian dan UU no. 34/2004 Tentang TNI). Artinya seorang Presiden yang oleh UUD diberikan kekuasaan (tertinggi) harus meminta persetujuan lembaga lain yang setara dengan presiden untuk menentukan bawahannya di eksekutif, walaupun pejabat itu bertanggung jawab kepada Presiden.
(Bersambung)
Artikel ini telah dimuat oleh Harian Suara Pembaruan, pada tanggal 24-25 Juli 2013, dengan judul “Menata (Kembali) Sistem Tata Negara: Menegakkan Sistem Presidensiil” (dalam dua bagian tulisan).

Penulis
Drs. Jakob Tobing, MPA. President Institut Leimena; Program Doctorate – Van Vollenhoven Institute, Rechtshogeschool, Universiteit Leiden; Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008); Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002); Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002); Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999); Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992); Anggota Panwaslu (1987); Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).
Responsible Citizenship
in Religious Society
Ikuti update Institut Leimena
